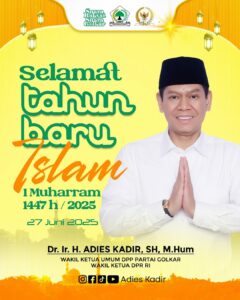Opini : Pendidikan Yang Membebaskan

Oleh :
Saifuddin Al Mughniy*
Pada prinsipnya pendidikan tidaklah lahir dari sebuah perjalanan sejarah yang stagnan, pendidikan tidaklah lahir dari perspektif evolusioner, namun pendidikan lahir dari sebuah perjalanan kemanusiaan yang revolusioner untuk membentuk satu kesatuan budaya yang kemudian disebut dengan peradaban. Artinya perkembangan epistemologi pengetahuan manusia telah menginjeksi untuk melatar belakangi lahirnya satu momentum dalam kehidupan manusia, baik ia sebagai individualis maupun ia selaku komunalistik.
Akar budaya adalah salah satu bagian terpenting yang mendorong lahirnya eko-humanisme yang berdampak pada siklus dan hukum dialektika yang menjadikan munculnya satu peradaban manusia. Oleh karena itu secara harfiah demitologi sains dan pengetahuan manusia telah menjadi mindset bagi perkembangan paradigma dan fase-fase perjalanan manusia dan lingkungannya. Hal lain yang coba kita terjemahkan bahwa hukum dialektika sejarah telah mengubah cara pandang orang terhadap orang lain dan lingkungannya.
Ini berarti bahwa manusia sudah mengalami masa-masa tarnsformasi social untuk dapat megetahui lingkungan dan dirinya sendiri serta berbagai kemungkinan yang mengancam habitatnya sebagai mahluk social. Ini penting di pahami supaya kita tidak salah menterjemahkan segala sesuatu yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan lingkungannya.
Kata pendidikan sebagai ungkapan yang cukup sederhana pada dasarnya telah memberikan ruang apresiasi serta penghargaan yang demikian baik. Hal ini tentu ditandai bahwa perkembangan sains dan tehnologi tidaklah secara tiba-tiba semuanya serba pengujian kebenaran melaui sintesa dan antitesa. Dan hal tersebut adalah bagian dari transformasi sains yang dilahirkan dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia.
Olehnya itu, menyingkap segala problematika pendidikan dalam halini saya akan mulai dari poin yang sangat mendasar, yakni jika kita tidak mentransendensikan gagasan tentang pendidikan yang dianggap sebagai transfer pengetahuan sebagai deskripsi atas realitas, maka kita tak akan pernah mempunyai kesadaran kritis yang akibatnya akan memperburuk buta huruf politik.
Jika kondisi ini telah benar-benar berubah sehingga kita dapat menentukan pilihan, maka kita harus mentransendensikan semua model pendidikan sehingga diperoleh model pendidikan dimana mengetahui (to know) dan merubah (transform), realitas merupakan syarat mutlak untuk membangun satu peradaban yang kritis. Namun yang terpenting adalah mentransendenkan praktek pendidikan yang membelenggu menjadi pola pendidikan yang membebaskan.
Dan saya bisa membayangkan bahwa tidak mungkin seorang guru dan dosen benar-benar melakukan praksis pembebasan jika masih mengikuti model pendidikan yang membelenggu. Dimana kemerdekaan untuk mengekspresikan sekaligus mengapresiasikan ide serta gagasannya dengan leluasa kalau kemudian dibatasi oleh jargon keterpenjaraan idealitas pemikiran yang tidak merdeka.
Walaupun pada prinsipnya guru yang berada di dalam model pendidikan yang membelengu ini masih menjadi guru bagi siswanya, mereka tidak lagi menjadi guru yang membebaskan, sehingga menjadi guru yng terpisah (Exlusive) dari siswanya. Sebaliknya guru terpaksa harus mengatakan kepada siswanya bahwa mereka “telah tiada” supaya mereka dapat lahir kembali sebagai siswa yang sebenarnya. Tanpa kematian dan kelahiran kembali pendidikan yang membebaskan tidak akan pernah terwujud. Sehingga memang perlu transformasi nilai-nilai sebagai bentuk transendensi ilmu pengetahuan manusia.
Untuk menghindari manipulasi dalam frame pendidikan, tentunya perlu gagasan yang cerdas dan kritis untuk bagaimana kemudian pendidikan diletakkan sebagai dasar filosofi yang berangkat dari psikologi kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Sehingga nampak jelas out put pendidikan yang coba di praktekkan. Hal ini dapat di amati dari gagasan-gagasan tokoh besar pendidikan kritis seperti Paulo Freire, yang selalu hadir dan menghadirkan paradigma pendidikan yang membebaskan.
Menurutnya, pendidikan tidak harus menjadikan murid atau siswa pintar, namun pendidikan harus menenamkan dua pola besar yaitu kedewasaan dan kemerdekaan dimana dua hal tersebut adalah jalan panjang bagi kehidupan pendidikan yang membebaskan. Pola pengajaran yang cendrung preskriptif (membelenggu) adalah cara belajar yang tidak bercermin pada akar filosofi pendidikan yang sebenarnya. Dimana praktek pengajaran memposisikan siwa sebagai obyek sehingga berkecendrungan membuat pola perilaku yang kaku, apatis, doktrinasi serta penghambaan siswa yang amat sangat berlebihan kepada gurunya.
Yang seharusnya posisi tersebut harus dibalik dalam dimensi pola pendidikan yang kritis dimana siswa harus menjadi subyek, sehingga peran-peran siswa begitu leluasa untuk menghadirkan ruang-ruang kosong yang selama ini terbelenggu dengan model pengajaran dan guru yang berkarakter feodal. Isolasi keilmuan nampak tersumbat dengan arogansi guru yang dibentuk oleh sistem manajemen sekolah yang otoriter dengan gaya guru tanpa senyum dan sangat berwibawa karena jaga gengsi sehingga siswa hanya mampu duduk manis dengan rasa takut yang berlebihan kemudian di sisipi doa ketidaktulusan …kapan yah guru ini pindah.
Fenomena ini saya kira sulitterbantahkan mengingat bagaimana peran guru (tenaga didik) mampu memainkan peran dan fungsinya selaku centrum transformasi keilmuan didalam rangka membangun dialektika dan hubungan yang dialogis antara subjek dengan objek. Komunikasi pendidikan sebagai sarana untuk hubungan dialogis itu tadi seharusnya di hadirkan untuk mewujudkan kemauan-kemauan stakeholders sebagai objek dari sebuah proses pendidikan paling tidak multikulturalisme bisa dijadikan sebagai sengketa ideologis didalam membangun akselerasi pendidikan yang jauh lebih bermartabat.
Hal ini tentunya bukan lagi menjadi sesuatu yang asing melihat responsive dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia sebagai dasar utama pembentukan kebudayaan dan peradaban yang manusiawi. Paradigma keterbelengguan perlahan-lahan ditinggalkan seiring dengan kemajuan bangsa-bangsa di dunia menuju sebuah pendidikan yang membebaskan.
Oleh karena itu dalam pandang progresifisme yang mengungkapkan bahwa tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis, untuk membuat siswa atau anak didik (peserta didik)lebih eektif dalam memecahkan berbagai persoalan yang disajikan dalam konteks empirisme pada umumnya. Secara karakteristik, progresifitas pendidikan yang bersifat duniawi yang menjelajah, aktif revolusioner, ini terutama mengarahkan orientasinya pada budaya liberalistik yang cendrung bertentangan dengan karakteristik budaya dan epistemologis timur.
Dan secara filosofis, progresifisme sesungguhnya di topang oleh gaya pragmatisme, dimana ia tidak memberikan jawaban-jawaban yang final (pasti) dan mengabsahkan kesimpulan-kesimpulannya melalui konsekuensi-konsekuensi perilaku yang ada dalam praktika sosial masyarakat dimana pendidikan itu berlangsung.
Namun akhirnya kaum rekonstruksionisme, yang berpandangan bahwa sekolah semestinya diabdikan kepada pencapaian tujuan kehidupan demokratis yang mendunia, secara filosofis kaum rekonstruksionisme yakin bahwa teori pada puncaknya tak terpisahkan dari latar belakang sosial dalam suatu era kesejarahan tertentu. Sebab fenomena rekonstruksionisme pendidikan lebih diarahkan pada perombakan sistem sosial yang berkecendrungan pada nilai-nilai pengetahuan manusia yang humanistik.
Namun semua itu tidak cukup hanya dengan kekuatan perubaha system yang ideal untuk menata pendidikan, tetapi yang terpenting bagaimana kemudian peran negara dalam hal ini pemerintah didalam mem-formulasi model pendidikan disamping anggran di sektorpenddikan di implementasikan sebagaimana amanat undang-undang sistem pendidikan nomor 20 Tahun 2003 sebesar 20 %.
Sebagai bentuk perbandingan beberapa negara Asia Tenggara dari hasil survey Pers Transparansi Internasional yang bermarkas di Berlin Jerman dari 6 negara yang di survey Indonesia masuk rangking ke 6 alokasi Anggaran Pendidikannya, justru anehnya Timor Leste dan Vietnam masih berada di atas Indoensia. Oleh sebab itu, pendidikan haruslah menjadi skala prioritas pembangunan karena dengan pendidikan cepat atau lambat akan menemukan hakekat sekaligus urgensi kebangsaan. Bahwa kalau ingin menciptakan pendidikan yang membebaskan minimal kita harus mampu menciptakan kemandirian dalam sektorsumber daya manusia yang mumpuni bukan tenaga pendidik hanya memburu “sertifikasi” tanpa peningkatan mutu pembelajaran baik yang mengajar maupun yang diajar. Sehingga terbangun interkoneksitas sumber daya pendidikan yang handal.**Demikian penuh harap***
“Jadikan semua orang sebagai guru
Dan jadikan semua tempat sebagai sekolah
Dan menjadi semua referensi sebagai sumber pengetahuan.”
Saifuddin Al Mughniy
Sekjen Forum Rakyat Indonesia
Analis Politik LKiS Research Development
Direktur Eksekutif OGIE institute Research and political Development
Anggota Forum Dosen Makassar
KADO HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2 MEI 2016