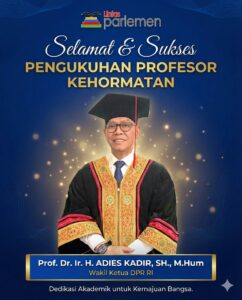BERAGAMA YANG DEWASA: Keimanan Tanpa Merendahkan

Munawir Kamaluddin Bersama Anies Baswedan (foto: pribadi)
Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara)
Apakah iman harus ditunjukkan dengan suara yang paling keras?
Apakah keyakinan menjadi lebih mulia ketika keyakinan orang lain direndahkan?
Mengapa atas nama agama, lisan begitu mudah melukai, sementara hati lupa bercermin?
Dan benarkah iman yang kokoh masih membutuhkan ejekan untuk merasa tinggi?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar gugatan intelektual, tetapi cermin batin yang seharusnya kita hadapi dengan jujur.
Sebab, di zaman ketika simbol agama begitu mudah dipamerkan, justru adab sering tercecer di jalanan.
Di tengah maraknya klaim kebenaran, kita lupa satu hal penting: iman yang dewasa tidak lahir dari penghinaan, tetapi dari kedalaman kesadaran.
Beragama sejatinya bukan perlombaan siapa paling lantang menyalahkan, melainkan perjalanan panjang menundukkan ego dan meninggikan akhlak.
Ketika iman masih merasa perlu merendahkan orang lain, bisa jadi yang sedang tumbuh bukan keimanan, melainkan rasa superior yang dibungkus dalil.
Allah SWT. telah mengingatkan sejak awal bahwa perbedaan adalah bagian dari sunnatullah, bukan alasan untuk saling mencela:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
“Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurāt: 13).
Ayat ini tidak hanya menegaskan asal-usul kemanusiaan yang sama, tetapi juga meruntuhkan klaim-klaim keagamaan yang berdiri di atas kesombongan.
Kemuliaan tidak diukur dari identitas, simbol, atau teriakan kebenaran, melainkan dari takwa yang menumbuhkan akhlak.
Karena itu, Al-Qur’an dengan tegas melarang penghinaan terhadap keyakinan lain, bukan karena melemahkan iman, tetapi justru untuk menjaga kemurnian iman itu sendiri:
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”(QS. Al-An‘am:108).
Ayat ini mengajarkan etika dakwah yang sangat dalam: kebenaran tidak boleh disampaikan dengan cara yang melahirkan kerusakan yang lebih besar.
Di sinilah letak kedewasaan beragama, yakni kemampuan membedakan antara keberanian menyampaikan kebenaran dan nafsu melampiaskan kebencian.
Rasulullah SAW. adalah teladan tertinggi dalam hal ini. Beliau tidak pernah menjadikan caci maki sebagai metode dakwah.
Bahkan, ketika dihina dan disakiti, beliau memilih jalan keluhuran akhlak:
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.”(HR. Ahmad).
Hadits ini adalah fondasi besar yang sering kita lupakan. Jika dakwah kita merusak akhlak, maka ia telah keluar dari misi kenabian.
Sebab, iman yang sejati tidak hanya benar secara teologis, tetapi juga indah secara etis. Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib RA. pernah berkata dengan kebijaksanaan yang melampaui zamannya:
النَّاسُ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ
“Manusia itu ada dua: saudaramu dalam agama, atau sesamamu dalam kemanusiaan.”
Ungkapan ini adalah pilar peradaban. Ia mengajarkan bahwa perbedaan iman tidak menghapus martabat kemanusiaan.
Menghina keyakinan orang lain berarti merobohkan jembatan kemanusiaan yang seharusnya kita rawat bersama.
Para ulama pun telah lama mengingatkan bahaya kesalehan yang kehilangan adab. Imam Al-Ghazali menulis:
لَيْسَ الْكَامِلُ مَنْ يَرَى عَيْبَ غَيْرِهِ، بَلِ الْكَامِلُ مَنْ يَرَى عَيْبَ نَفْسِهِ
“Bukanlah orang yang sempurna itu yang melihat aib orang lain, tetapi yang melihat aib dirinya sendiri.”
Maka, beragama yang dewasa adalah ketika iman menjadikan seseorang lebih rendah hati, lebih lembut ucapannya, dan lebih dalam empatinya, bukan sebaliknya.
Ketika iman masih sibuk menunjuk kesalahan orang lain, bisa jadi ia belum sempat menyentuh ruang batin yang paling sunyi, ruang muhasabah diri.
Di titik inilah kita perlu bertanya ulang, dengan kejujuran yang mungkin menyakitkan, Apakah agama kita telah membuat orang lain merasa aman?
Ataukah justru takut, terancam, dan terhina?
Sebab, keimanan tanpa adab hanya melahirkan kegaduhan, sementara keimanan yang dewasa melahirkan keteduhan. Ia tidak berisik, tetapi berakar. Tidak merendahkan, tetapi mengangkat martabat sesama.
Dan mungkin, justru di situlah tanda iman yang sesungguhnya, ketika kita mampu berkata benar tanpa melukai, meyakini dengan teguh tanpa merendahkan,dan beragama dengan penuh cinta tanpa kehilangan prinsip.
#Wallahu A’lam Bish-Shawab