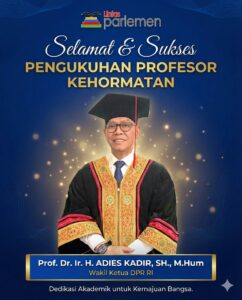KETIKA DEMOKRASI TIDAK LAGI HUMANIS: Jalanan Menjadi Arena Amuk Massa

Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara)
Apakah demokrasi masih menjadi rumah bagi suara manusia, atau kini hanya panggung di mana amarah berakrobat dan luka sosial dipertontonkan?
Apakah aksi massa masih lahir dari kesadaran untuk memperbaiki keadaan, atau hanya menjadi gemuruh tanpa kendali yang memaksa jalanan menelan martabat kita sedikit demi sedikit?
Dan yang lebih penting, siapakah yang sesungguhnya paling terluka ketika ruang demokrasi kehilangan sentuhannya yang humanis, apakah mereka yang berkuasa, atau kita yang berjalan di bawah bayang-bayang ketidakpastian?
Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah kita untuk menatap cermin sosial yang tak pernah berbohong.
Demokrasi memang dibangun atas nama demos, rakyat, tetapi demokrasi tanpa sentuhan nilai-nilai kemanusiaan ibarat tubuh yang kehilangan ruh.
Ia masih berdiri secara formal, tetapi rapuh secara moral. Ketika institusi melemah, ketika keadilan dirasa hanya milik sebagian, ketika saluran aspirasi tersumbat oleh kepentingan sempit, maka jalanan mulai bergetar, berubah menjadi tempat di mana suara yang tak didengar mencari teriakannya sendiri.
Namun suara tanpa etika mudah menjelma amukan. Ruang publik, yang seharusnya menjadi taman dialog, sering kali berubah menjadi gelanggang benturan.
Di sanalah ketegangan merayap dari bisik-bisik ke pelataran kota, dari keluhan menjadi tumbukan, dari kecemasan menjadi kobaran.
Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa protes paling rawan berubah menjadi kekerasan ketika negara merespons dengan represi atau ketika massa bergerak spontan tanpa organisasi yang matang.
Ketika dua kondisi ini bertemu, demokrasi kehilangan wajah lembutnya.
Islam sejak awal menempatkan keseimbangan antara keberanian menyuarakan kebenaran dan keharusan menjaga kemaslahatan.
Allah berfirman dalam ayat yang menjadi fondasi moral peradaban:
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; kamu menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar…” (QS. Ali Imran: 110)
Ayat ini bukan sekadar seruan normatif, ia adalah peringatan bahwa tujuan baik harus ditempuh dengan cara yang ma’ruf pula.
Sebuah riwayat yang merukaka pesan moril megajarkan:
مَن أمرَ بمعروفٍ، فليَكُن أمرُهُ بمعروفٍ.
“Sesiapa yang menyuruh kepada perkara makruf, maka jadikanlah suruhannya itu dengan cara makruf pula.”
Rasulullah SAW. menegaskan prinsip yang sangat ringkas namun amat mendalam:
لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ
“Tidak boleh menimbulkan mudharat dan tidak boleh membalas mudharat dengan mudharat pula.”
Hadits singkat ini adalah batas etika yang menjaga agar perjuangan tidak berubah menjadi penghancuran, agar protes tidak menjadi pelampiasan, dan agar aspirasi tidak menjelma kerusakan.
Ketika aksi yang diniatkan menuntut keadilan justru mencederai kehidupan orang kecil, pedagang yang kehilangan tempat kerja, anak-anak yang terjebak ketakutan, atau pekerja harian yang merugi karena kota lumpuh, maka keadilan yang dicari berubah menjadi paradoks yang menyakitkan.
Di sinilah kita melihat wajah sosial yang paling mudah terluka. Dalam setiap kerusuhan, mereka yang paling menderita bukanlah elite, bukan pula aktor politik yang jauh dari debu kehidupan sehari-hari.
Korban sesungguhnya adalah rakyat kecil , mereka yang tak pernah terlibat dalam perdebatan di ruang parlemen tetapi merasakan langsung dampaknya di tengah jalanan.
Kehilangan barang dagangan, rusaknya fasilitas publik, lumpuhnya ekonomi harian , semua menjadi luka yang tak pernah mendapat panggung berita.
Jalanan yang semula simbol kebebasan kini menjadi momok yang mengoyak kepercayaan sosial. Di sana solidaritas melemah, curiga tumbuh, dan trauma menetap dalam diam.
Di sisi lain, negara pun ikut terjebak dalam dilema. Bila ia terlalu keras, ia dituduh represif, bila ia terlalu lunak, ia dituding lemah. Legitimasi negara tercabik ketika penanganan yang salah memicu gelombang kekerasan lanjutan.
Maka demokrasi pun berada di ambang paradoks, sistem yang seharusnya menjamin partisipasi berubah menjadi arena konflik, sementara prinsip humanisme yang menjadi jantung demokrasi justru memudar.
Para ilmuwan sosial menegaskan bahwa kekerasan massa biasanya lahir dari akumulasi ketidakadilan yang tidak ditangani secara struktural. Ketimpangan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap peradilan, dan polarisasi politik menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar.
Ketika unsur-unsur ini bertemu dengan provokasi, baik dari kelompok kepentingan maupun aktor yang ingin memancing kekacauan, maka jalanan kehilangan akal sehatnya.
Dalam khazanah Islam, para ulama salaf menekankan bahwa menegur kemungkaran harus dilakukan dengan hikmah, bukan dengan kemarahan yang membabi buta. Ibn al-Qayyim mengingatkan bahwa:
إنَّ إنكارَ المُنكَرِ إذا أدَّى إلى ما هو أنكرُ منه فهو منهيٌّ عنه.
“Menghilangkan kemungkaran yang menyebabkan kemungkaran lebih besar adalah sesuatu yang terlarang.”
Peringatan ini bukan untuk membungkam aspirasi, tetapi untuk mengarahkan agar perjuangan tidak melukai tujuan utamanya. Sebab keadilan yang ditegakkan dengan cara yang bathil hanyalah keadilan palsu.
Pada akhirnya, kita perlu menyadari bahwa demokrasi hanya dapat hidup bila manusia di dalamnya hidup dengan adab. Jalanan hanya menjadi ruang kebebasan ketika kita mengakui bahwa kebebasan seseorang selalu berdampingan dengan keselamatan orang lain.
Kerusuhan yang merusak fasilitas publik, melukai sesama, atau memaksakan kehendak dengan ancaman adalah isyarat bahwa demokrasi telah kehilangan salah satu unsurnya yang paling mendasar: kemanusiaan.
Maka langkah menuju perbaikan tidak dapat dilakukan hanya dengan regulasi, tetapi juga dengan penyembuhan moral.
Kita memerlukan pendidikan politik yang menanamkan empati, bukan sekadar strategi memenangkan kekuasaan.
Kita membutuhkan mekanisme dialog yang membuka ruang agar rakyat merasa didengar, bukan hanya ditertibkan.
Kita membutuhkan elite yang memimpin dengan keteladanan, bukan dengan kalkulasi elektoral semata.
Dan kita membutuhkan rakyat yang menuntut dengan nurani, bukan dengan kemarahan yang mudah diprovokasi.
Demokrasi tidak akan runtuh hanya karena perbedaan pendapat, tetapi ia akan hancur ketika kita berhenti melihat manusia lain sebagai manusia.
Bila jalanan sudah menjadi arena amuk massa, itu berarti ada luka sosial yang mendesak untuk diobati. Kita tidak sedang membahas sekadar protes, melainkan kondisi batin sebuah bangsa.
Jika kita mampu mengembalikan demokrasi kepada ruhnya, ruang dialog, ruang kemanusiaan, ruang martabat , maka jalanan akan kembali menjadi tempat di mana suara terdengar tanpa harus melukai.
Dan jika tulisan ini membuat hatimu bergetar atau membuatmu menatap keadaan sosial dengan lebih gelisah, itu pertanda bahwa masih ada ruang untuk perubahan.
Perubahan yang lahir bukan dari amarah, tetapi dari kesadaran bahwa bangsa ini hanya dapat berdiri tegak ketika kita memilih menjadi manusia sebelum menjadi massa.
#Wallahu A’lam Bish-Shawab