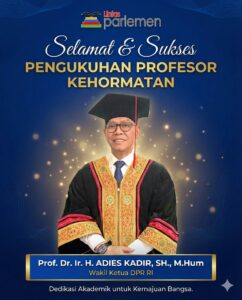PERSAUDARAAN KEMANUSIAAN: Nafas Panjang Peradaban di Era Ego Kolektif

Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara)
Peradaban manusia berdiri dan bertahan bukan semata oleh kekuatan politik, kemajuan teknologi, atau keunggulan ekonomi, melainkan oleh kemampuan manusia menjaga martabat sesamanya.
Ketika kemajuan tidak lagi diiringi empati, dan identitas berubah menjadi alat penyingkiran, peradaban mulai kehilangan ruhnya.
Di titik inilah ego kolektif tumbuh, bukan sebagai kesadaran bersama untuk kebaikan, tetapi sebagai kekuatan yang menegaskan batas, mempersempit pandangan, dan mengerdilkan kemanusiaan.
Ego kolektif menjadikan perbedaan sebagai ancaman, bukan anugerah. Ia melahirkan sikap saling curiga, mudah menghakimi, dan gemar meniadakan.
Dalam suasana seperti ini, persaudaraan kemanusiaan kerap dianggap lemah, bahkan dicurigai sebagai pengaburan identitas.
Padahal, justru persaudaraan kemanusiaanlah yang menjadi nafas panjang peradaban, penyangga sunyi yang menjaga umat manusia agar tidak tenggelam dalam konflik yang diwariskan lintas generasi.
Islam hadir bukan sebagai agama yang menyempitkan dunia, tetapi sebagai risalah yang meluaskan kehidupan.
Allah SWT. menegaskan kemuliaan manusia sebagai fondasi awal peradaban:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.”
(QS. Al-Isrā’: 70).
Kemuliaan ini tidak disyaratkan oleh kesamaan keyakinan. Ia melekat pada status manusia sebagai ciptaan Allah.
Karena itu, merendahkan manusia lain, apa pun identitasnya, adalah bentuk pengingkaran terhadap kehendak Tuhan yang memuliakan.
Islam tidak meniadakan perbedaan, tetapi menempatkannya dalam kerangka pengenalan dan kerja sama kemanusiaan. Al-Qur’an menyatakan:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ… لِتَعَارَفُوا
“Wahai manusia, sungguh Kami menciptakan kamu… agar kamu saling mengenal.”( QS. Al-Hujurāt: 13)
Kata لتعارفوا ( Lita’arafu) menandakan proses panjang yang melibatkan kesadaran, kesabaran, dan penghormatan.
Ia menolak logika ego kolektif yang tergesa-gesa menilai dan menutup ruang dialog.
Dalam pandangan Islam, perbedaan bukan alasan untuk saling meniadakan, tetapi jalan untuk memperdalam kemanusiaan.
Prinsip inilah yang melahirkan konsep besar Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana ditegaskan Allah SWT:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.”
(QS. Al-Anbiyā’: 107)
Rahmatan lil ‘alamin tidak dibatasi oleh iman, suku, atau bangsa. Ia mencakup seluruh makhluk, manusia dengan segala perbedaannya, bahkan alam yang menopang kehidupan.
Maka, setiap Muslim sejatinya dipanggil untuk menghadirkan agama sebagai sumber keteduhan, bukan kegaduhan; sebagai jembatan, bukan tembok.
Rasulullah SAW. mempraktikkan prinsip ini dalam kehidupan nyata. Ketika beliau berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi, tindakan itu adalah pernyataan peradaban, bahwa kemanusiaan tetap layak dihormati, bahkan setelah nyawa berpisah dari raga:
أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟
“Bukankah dia juga manusia?”
(HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam satu kalimat, Nabi SAW. menegaskan bahwa melihat manusia dengan kacamata iman berarti melihatnya sebagai ciptaan Allah yang memiliki hak atas penghormatan.
Inilah wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin, yakni tenang, berwibawa, dan penuh kasih.
Kesadaran ini ditegaskan pula oleh Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib RA.:
النَّاسُ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ
“Manusia itu dua: saudaramu dalam agama, atau sesamamu dalam penciptaan.”
Ungkapan ini adalah fondasi etika sosial Islam. Ia mengajarkan bahwa sesama manusia, apa pun keyakinannya. bukanlah objek kebencian, melainkan objek pengabdian dan ladang ibadah.
Melayani manusia, menjaga martabatnya, dan meringankan bebannya adalah bagian dari jalan menuju ridha Allah.
Islam memandang hubungan sosial bukan sekadar relasi horizontal, tetapi sebagai ibadah yang bernilai vertikal.
Rasulullah SAW. bersabda:
أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
“Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani).
Hadits ini tidak membedakan siapa yang ditolong. Manfaat bagi manusia (siapa pun dia), adalah jalan menuju kemuliaan di sisi Allah.
Inilah logika ibadah sosial dalam Islam: melihat sesama bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sarana mendekat kepada Tuhan.
Para ulama memahami bahwa rusaknya relasi kemanusiaan adalah tanda runtuhnya peradaban. Ibn Khaldun menegaskan:
الظُّلْمُ مُؤْذِنٌ بِخَرَابِ الْعُمْرَانِ
“Kezaliman adalah pertanda hancurnya peradaban.”
Kezaliman hari ini sering hadir dalam bentuk yang halus: pembenaran kolektif untuk merendahkan, menyingkirkan, dan menutup empati atas nama identitas.
Ketika ini dibiarkan, agama kehilangan ruh rahmatnya, dan iman tereduksi menjadi simbol tanpa akhlak.
Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kedewasaan iman selalu dimulai dari perbaikan diri:
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ اشْتَغَلَ بِإِصْلَاحِهَا عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ
“Siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk memperbaikinya daripada mencari-cari aib orang lain.”
Dalam kesadaran inilah persaudaraan kemanusiaan menemukan maknanya yang paling dalam. Ia bukan sekadar etika sosial, melainkan jalan ibadah.
Menghormati manusia adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Menjaga kemanusiaan adalah cara merawat agama agar tetap hidup sebagai rahmat.
Di tengah era ego kolektif, persaudaraan kemanusiaan adalah keteguhan yang sunyi namun menentukan. Ia menjaga agar peradaban tetap bernapas panjang, melalui keadaban, keteladanan, dan kasih sayang.
Sebab hanya dengan itulah iman menemukan kemuliaannya, dan manusia menemukan jalan menuju ridha Allah.
#Wallahu A’lam Bish-Shawab